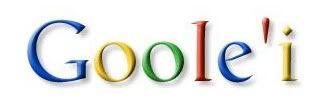menteoritisasi dan merekomendasi negara sekuler, pemisahan antara kalam ilahiyah
dalam dunia politik. Akibat teorinya tersebut dia harus menanggung resiko
dipecat dari jabatannya sebagai hakim syariah oleh majelis ulama tertinggi di
Mesir serta dicopot gelar ustadnya (baca: professor) pada Universitas Al-Azhar.
Setidaknya ada dua tipologi—meminjam Donald Eugene Smith—untuk
mengklasifikasikan para pemikir Islam dalam diskursus hubungan antara agama dan
negara. Pertama, para intelektual organik; mereka mengklaim perlunya penyatuan
antara dimensi ilahiyah dalam politik, karena agama (Islam) mempunyai jangkauan
yang luas dan meliputi seluruh spektrum kehidupan. Menurut eksponen organik
ini, Islam Huwa Ad-diin Wa Ad-dawlah (Islam adalah penyatuan antara
agama dan negara). Para intelektual organik ini
terepresentasikan oleh Sayyid Qutb, Rasyid Ridha dan Al-Maududi. Kedua, para
intelektual sekuler, mereka mengklaim keharusan pemisahan antara agama dan
negara. Hal ini untuk menjaga dan melestarikan eternalitas dan kesempurnaan
agama (baca:Islam). Dalam perspektif kedua ini muncul Ali Abdurraziq.
Baru belakangan ini Bahtiar Effendy melengkapi dua perspektif dikotomik di atas dengan
perspektif ketiga, intelektual diferensiatif, yang mengklaim agama sebagai
basis moral dan etika dalam kehidupan politik. Dalam deretan ketiga ini muncul
Muhammad Abduh, Ibnu Khaldun, dan Filosof muslim paling berpengaruh pada abad
ini, Muhammad Iqbal.
Memang harus diakui bahwa pemikiran tentang pemisahan antara agama dan negara tidak
mempunyai preseden sejarah dalam kehidupan Nabi. Swidler, misalnya, mengatakan
bahwa praktek sekularisasi hanya ada dalam pemikiran Kristen pada abad
pertengahan, yang dari situ kemudian menimbulkan revolusi industri dan era
pencerahan di beberapa negara belahan Eropa lainya.
Meski begitu, tesis yang dibangun oleh Ali Abdurraziq tentang sekularisasi lebih
didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: apakah kekhalifahan
memang diperlukan? Apakah memang ada pemerintahan yang Islami? Dan dari manakah
sumber legitimasi kekuasaan? Dari rakyat ataukah dari Tuhan?
Dari beberapa pertanyaan tersebut kemudian dia membangun argumentasi yang ditulis dalam karya magnum opusnya “al-Islam wa al-Ushul al-Hukmi: Bahstun Fi al-Khilafati wa al-Hukumati fi al-Islam” (Islam dan Sumber-sumber Kekuasaan Politik: Kajian tentang Khilafah
dan Kekuasaan dalam Islam). Dalam bukunya tersebut dia menyimpulkan beberapa
hal: (1) Nabi tidak membangun negara dalam otoritas spiritualnya. (2) Islam
tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena itu umat Islam
bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi
kondisinya. (3) Tipologi pemerintahan yang dibangun setelah wafatnya Nabi,
tidaklah memiliki dasar-dasar dalam Alquran dan Alhadis. Ia semata-mata “karya
kreatif-imaginatif” bangsa Arab yang kemudian dinaikkan derajatnya menjadi sistem
khilafah yang dilegitimasi dari doktrin-doktrin agama. (4) Sistem ini (baca:
khilafah) telah menjadi tipuan bagi sebagian besar persoalan-persoalan dunia
Islam karena dalam realitasnya telah menjadi pendukung tirani di negara-negara
Islam.
Harus diakui bahwa setting sosio-politik pada waktu itu turut mengambil bagian
dalam usaha Abdurraziq untuk mengkonstruksi tesis-tesis yang telah ditulisnya.
Bahwa pembubaran Kemal Attaturk atas otoritas kekhalifahan Ottoman pada
1923-1924 didasarkan pada penilaian bahwa lembaga ini—terutama otoritas keulamaanya—telah
mengabdi kepada kepentingan Sultan atau penguasa, dengan penerimaan mereka atas
perjanjian damai yang memalukan rakyat Islamabad tersebut.
Dari beberapa tesis yang telah dibangunnya, sembari mengacu kepada mufassir laiknya
Al-baidhawi dan Zamakhsyari (seorang mufassir yang berfaham muktazilah dan
pemilik kitab tafsir “al-Kasyaf”), Abdurraziq menafsirkan kata “Ulil Amri”
dengan penafsiran “Sahabat Nabi” atau “Ulama”. Oleh sebab itu, dia menolak
bahwa Nabi adalah seorang raja. Nabi adalah pemimpin spiritual ansich. Dari
titik ini, Abdurraziq melakukan kritik terhadap kecenderungan idealistik dan
formalistik yang telah dipraktekkan oleh intelektual organik di atas. Pemikiran
formalistik seringkali menampilkan kecenderungan bertindak secara idealistik
dengan melakukan idealisasi nilai-nilai Islam untuk kemudian secara intotum
di adopsi oleh negara. Pemikiran ini pernah dilontarkan oleh Alfarabi dengan
“Al-madinah Al-fadhilah”-nya yang terkesan idealistik dan tidak mempunyai
preseden sejarah (ahistoris).
Teori sekularisasi ini, menurut penulis, masih menemukan relevansinya, khususnya dalam konteks keindonesiaan.
Masih minimnya negara-negara muslim demokratis di belahan dunia (termasuk Indonesia), merupakan bukti sejarah betapa
porak porandanya s-stem demokrasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Samuel Huntington dalam The Third Wafe mengatakan bahwa selain
konfusianisme Islam diragukan kompatibilitasnya dengan demokrasi. Memang,
sebagaimana aku Huntington, apabila diinterpretasikan secara
benar oleh pemeluknya, maka ajaran-ajaran normatif Islam sangat kompatibel
sekali dengan substansi demokrasi. Namun, realitas empiris dunia Islam
mengatakan inkompatibilitasnya dengan demokrasi.
Laporan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Freedom House, desember 2001, dengan tajuk
“Freedom in the World 2001-2002”, menyebutkan bahwa di antara negara-negara di
dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam kategori demokratis. Paling
banter, di antara negara Islam hanya ada yang masuk dalam kategori “partly
free” (setengah demokratis), seperti: Indonesia, Jordan, Kuwait, Maroko, Turki dan Malaysia. Sedangkan Aljazair, Iran, Mesir, Libanon, Uni Emirat Arab, Oman,
Pakistan, Qatar, Bahrain, Afganistan, Lybia, Iraq, Arab Saudi, Sudan dan Syiria
masuk dalam kategori “not free” (tidak demokratis). Yang lebih dramatis lagi,
negara seperti Korea Utara, yang dinilai tidak demokratis, pada dasarnya
mempunyai kemungkinan tiga kali lebih besar dibandingkan Iran (yang sama tidak demokratisnya), menjadi negara
demokrasi.
Dalam konferensi internasional yang berlangsung di Jakarta, 18-19 Maret 2002, dengan
tema “The Challenge of Democracy in the Muslim World”, tidak kurang dari 15
ahli dengan reputasi internasional mencoba mendiagnosa kasus-kasus pengalaman
demokrasi di negara-negara muslim. Dari pakar-pakar yang hadir bisa
dikategorikan secara sederhana dalam dua kelompok: optimis dan atau pesimis
terhadap melihat kompatibilitas Islam dan demokrasi. Lisa Anderson, Richard K.
Herman dan Bill Fierman masuk dalam kelompok pertama. Sementara Azyumardi Azra,
R. William Liddle masuk kelompok kedua. Sikap pesimistik tersebut masuk akal,
bila menyimak laporan terakhir dari “Freedom House” di atas. Ada beberapa faktor menurut Azra; pertama,
kelemahan dalam infrastruktur dan prasyarat pertumbuhan demokrasi. Kedua:
masih kuatnya pandangan normatif-teologis tentang kesatuan al-Diin (agama)
dan al-Dawlah (negara). Ketiga, masih dominanya kharisma, yaitu
kultur politik tradisional yang berpusat pada kharisma kyai, yaitu kyai yang
ditaqlidi secara buta oleh sebagian ummat Islam. Keempat, kegagalan
negara-negara muslim yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan
demokrasi secara genuine dan otentik. Kelima, ketunakuasaan civil
society vis a vis penguasa.
Karena itulah, dari 121 negara yang memiliki pemerintahan yang dipilih secara
demokratis, kita hanya menyumbang 11 negara dari 47 (23%) negara muslim yang
disurvei. Ini berbanding terbalik dengan negara non-muslim, dari keseluruhan
145 negara, 110 di antaranya demokratis (76%). Anehnya, negara-negara pecahan
Uni Soviet yang mayoritas non-muslim seperti Ukraina, cepat mengadopsi kultur
demokrasi. Sebaliknya, negara Kazakstan, Uzbekistan, dan Tajikistan yang mayoritas muslim tak kunjung demokratis.
Jose Casanova dalam bukunya Public Religion in The Modern World (Chicago: The
University of Chicago Press, 1994) mendedahkan dengan sangat bagus sekali tiga
implikasi dari sekularisasi, pertama: The decline of religion (kemerosotan
peran agama). Inilah pemahaman yang dianut oleh sebagian besar muslim tentang
definisi sekularisasi, sehingga ada “stigma” yang mengharuskan kita untuk takut
terhadap sekularisasi. Kedua, sekularisasi bermakna “diferensiasi”, yaitu
adanya pemisahan yang jelas antara ranah agama dan ranah politik, ekonomi,
maupun ilmu pengetahuan. Ketiga: sekularisasi mengimplikasikan “privatisasi”,
yaitu pemisahan antara ruang publik dan ruang prifat. Ruang publik adalah ruang
di mana setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat
melakukan kontestasi secara bebas dan fair. Kata kunci dalam ruang publik
adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat
dalam kontestasi tersebut. Sedangkan ruang prifat adalah ruang di mana seseorang
bisa hidup dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak
lain. Inilah wilayah “independen dan otonom” di mana seseorang bebas untuk
memilih atau tidak memilih atas segala sesuatu. Dalam ruang tersebut
dimungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, tanpa adanya intervensi dari
institusi luar. Dalam konteks sekuler Islam menempati locus-nya di ruang prifat.
(Rumadi, Kompas, 23
April 2002)
Implikasi penting—yang perlu kita petik dari pemikiran Abdurraziq dalam konteks keindonesiaan---adalah
pandangan Abdurraziq mengenai kekuasaan sebagai sebuah instrumen (baca: wasilah/alat).
Dari perspektif Weberian dia menggunakan “rasionalitas instrumental” dalam
memandang kekuasaan (politik). Artinya, dia menjadikan politik sebagai alat dan
bukanlah tujuan yang segala-galanya. Sehingga kekuasaan (politik) adalah
sesuatu yang profan dan negotiable serta diperlukan partisipasi rakyat
untuk selalu melakukan kontrol terhadapnya.
Sedangkan agama (Islam) dipandang sebagai sesuatu yang perlu, yaitu dalam fungsinya
sebagai etika agama, moralitas agama, dan common good (al-mashalih
al-mursalah). Sayang, sekularisasi dalam paradigma mayoritas umat Islam masih
tetap, konstan, dan tidak bergeser dalam definisi “The Decline of Religion”
(kemerosotan peran agama), tanpa memperhatikan lebih detail lagi fenomena
kompleks yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Sadiq Jalal al-Azm dalam
artikelnya, Is Islam Secularizable? mangatakan bahwa secara dogmatik
sekularisasi sulit dipraktekkan dalam dunia muslim, tetapi sangat mungkin dalam realitas empiris. Wallahu A’lam. []
Source: islamlibCom